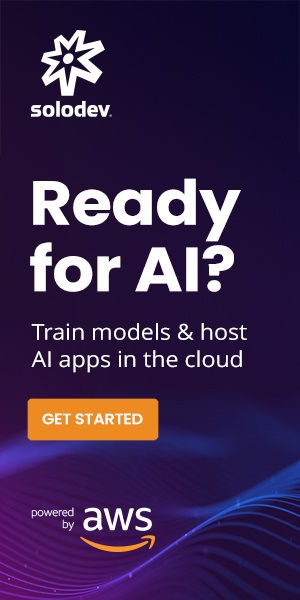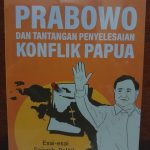Korupsi Desa Dibalik Kata “Uang Rokok”
Korupsi Desa Dibalik Kata “Uang Rokok”
RATAS.id – Indonesia sering memandang korupsi sebagai penyakit besar yang hanya hidup di gedung kementerian, DPR, atau ruang sidang kasus miliaran bahkan triliunan. Padahal, sesungguhnya korupsi paling mendasar ada di desa, tempat uang negara pertama kali bertemu dengan rakyat kecil. Di sana praktik busuk ini tumbuh dari hal sepele yang dianggap budaya uang rokok.
Kalimat “buat uang rokok, Pak” yang terdengar ringan, ternyata adalah pintu masuk normalisasi kejahatan. Jumlahnya puluhan ribu rupiah, diberikan dengan senyum, diterima dengan senyum, lalu hilang begitu saja. Tidak ada yang marah, tidak ada yang melapor. Dari titik inilah budaya korupsi desa dilatih sesuatu yang salah dibungkus sebagai tanda terima kasih. Lalu masyarakat, dengan keterpaksaan atau rasa segan, ikut memelihara kebiasaan itu.
Uang rokok yang dibiarkan wajar perlahan melahirkan pembenaran untuk mark-up biaya pembangunan, laporan kegiatan fiktif, hingga pengadaan barang yang tidak pernah ada. Jika yang kecil dianggap lumrah, yang besar tinggal menunggu giliran. Inilah wajah desa korup tempat kejahatan dimulai dari recehan, tapi berakhir dengan menggerogoti miliaran rupiah.
Dana Desa Jadi Petaka
Pemerintah sejak 2015 menjadikan dana desa sebagai tonggak pembangunan dari bawah. Tahun 2023 saja, jumlah dana desa yang digelontorkan mencapai Rp68 triliun, tersebar ke 75.265 desa dengan rata-rata Rp903 juta per desa. Jika dana sebesar itu dikelola jujur, tentu desa bisa punya jalan mulus, jembatan kuat, irigasi lancar, puskesmas layak, hingga usaha mikro yang bertumbuh.
Namun realitasnya, dana desa justru menjadi santapan empuk bagi para kepala desa dan lingkaran pendukungnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa, menjadikannya sektor dengan jumlah kasus terbanyak dibanding sektor lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp162,2 miliar.
Angka ini memang tampak kecil jika dibandingkan total kerugian korupsi nasional tahun yang sama, yakni Rp28,4 triliun. Tetapi perbandingan itu menyesatkan. Karena bagi warga desa, kehilangan miliaran rupiah bukan sekadar soal angka, melainkan pupusnya mimpi sederhana jalan tak lagi berlubang, sawah tak lagi kekeringan, atau anak-anak tak lagi belajar di bangunan reyot. Dana yang seharusnya jadi penyambung harapan berubah menjadi pesta kecil segelintir orang berpengaruh.
Patronase Politik Uang di Level Desa
Korupsi desa bukanlah perbuatan tunggal. Kepala desa tidak pernah berjalan sendirian. Mereka terikat pada jaring patronase tim sukses yang membantu memenangkan pilkades, kerabat yang harus dibalas jasa, atau kelompok yang perlu dipelihara loyalitasnya. Maka ketika dana desa turun, proyek pembangunan dibagi sesuai peta dukungan politik.
Jalan dibangun di kampung pendukung, proyek pengadaan material dikuasai kerabat, dan laporan keuangan diatur sedemikian rupa agar seolah-olah program berjalan. Musyawarah desa yang seharusnya forum demokratis berubah menjadi panggung formalitas. Semua sudah disusun, warga hanya diminta hadir, mendengarkan, lalu pulang dengan perasaan percuma.
Patronase ini yang membuat dana desa jarang tepat sasaran. Infrastruktur sering setengah jadi, bahkan fiktif. Pengadaan bahan bangunan diatur oleh makelar lokal yang dekat dengan kekuasaan tidak jarang harga dinaikkan dua hingga tiga kali lipat dari nilai pasar lalu ketika warga bertanya mengapa proyek tak selesai, jawabannya diplomatis dana tidak cukup, prosedur rumit, atau menunggu pencairan tahap berikutnya. Padahal sesungguhnya, anggaran sudah terlebih dahulu habis dibagi ke lingkaran dalam.
Dana Desa Benih Korupsi
Data ICW menunjukkan pada 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka di seluruh Indonesia. Namun hanya 6 kasus yang diproses dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Artinya, sebagian besar pelaku tetap bisa menyimpan hasil korupsinya dengan aman, menunggu hukuman berakhir, lalu kembali menikmati kekayaan.
Di desa, situasi lebih memuakkan ada kepala desa yang terbukti menggelapkan dana pembangunan, dihukum ringan, bahkan setelah bebas bisa kembali maju pilkades. Alasannya sederhana masih populer, masih dianggap berjasa, dan masyarakat sudah terbiasa memaafkan. Padahal, inilah yang membuat efek jera tidak pernah hadir. Desa menjadi laboratorium impunitas, tempat maling uang rakyat bisa kembali dipuja karena membagi sedikit “rezeki” ke warga.
Lebih menyakitkan lagi, masyarakat yang mencoba melapor sering kali tertekan oleh budaya sosial. Melaporkan kepala desa sama saja dengan melawan tetangga sendiri mendapat resiko dikucilkan, dianggap pengkhianat, hingga ancaman langsung membuat warga lebih memilih diam. Korupsi pun dibiarkan berjalan dengan dalih harmoni sosial.
Korupsi desa tidak hanya merusak keuangan negara ia menghancurkan sendi demokrasi lokal. Musyawarah desa kehilangan makna, warga kehilangan semangat partisipasi, dan generasi muda tumbuh dengan mental permisif melihat uang publik bisa diutak-atik tanpa masalah.
Korupsi kecil di desa ibarat racun yang meresap ke akar ia membuat warga tidak percaya pada pemimpin, tidak percaya pada proses, dan akhirnya apatis. Akibatnya, desa yang seharusnya menjadi fondasi negara justru menjadi titik rapuh. Pohon besar bernama Indonesia bisa tumbang jika akarnya digerogoti setiap hari.
Transparansi Hanya Formalitas
Pemerintah mencoba menegakkan transparansi dengan mewajibkan papan informasi anggaran di setiap desa. Namun papan itu sering hanya deretan angka yang sulit dipahami warga. Lebih dari itu, siapa yang berani memverifikasi? Warga tidak punya akses, tidak punya keberanian, dan tidak punya ruang untuk mengkritik. Maka papan informasi menjadi sekadar hiasan, bukti formal bahwa aturan dijalankan, padahal kenyataannya tak pernah ada keterbukaan.
Sistem pengawasan digital seperti Siswakeudes yang diperkenalkan KPK seharusnya bisa menjadi jalan keluar. Tapi selama implementasi hanya bersifat opsional, desa akan tetap jadi wilayah gelap. Tanpa keterbukaan yang bisa diakses publik, jangan pernah berharap korupsi di desa akan berhenti.
Kita sering menganggap korupsi desa sebagai kasus kecil. Tetapi coba lihat dampaknya di lapangan. Jalan tetap berlubang, sawah tetap kekeringan, jembatan tetap reyot, puskesmas tak pernah rampung, dan anak-anak sekolah belajar di kelas bocor. Itu bukan karena negara miskin, melainkan karena uang yang seharusnya hadir di sana sudah hilang di meja tanda tangan.
Lebih parah lagi, budaya permisif ini merusak generasi. Anak-anak tumbuh dengan melihat bahwa memberi uang rokok adalah hal biasa. Mereka akan menganggap suap adalah wajar, bahwa korupsi adalah bagian dari hidup. Jika ini dibiarkan, desa tidak hanya melahirkan warga apatis, tetapi juga calon pejabat yang siap meneruskan tradisi kotor itu di level lebih tinggi.
Berani Melawan Budaya Uang Rokok
Membangun Indonesia dari desa hanya akan jadi slogan kosong jika desa terus dibiarkan menjadi ladang korupsi. Kepala desa yang terbukti korupsi harus dihukum maksimal, dilarang mencalonkan diri lagi, dan hartanya disita. Tidak ada alasan untuk memberi keringanan, karena korupsi di desa adalah pengkhianatan terhadap rakyat paling miskin.
Lebih jauh, warga desa harus berani melawan budaya uang rokok ini bukan sekadar soal nominal kecil, melainkan simbol perlawanan terhadap lingkaran setan. Menolak uang rokok adalah langkah awal menolak normalisasi korupsi. Partisipasi warga harus dihidupkan kembali. Musyawarah desa harus menjadi forum kritis, bukan sekadar seremonial. Karang taruna, kelompok tani, dan pemuda harus ikut mengawasi jalannya anggaran.
Jika desa berhasil dibersihkan dari praktik korupsi, Indonesia akan punya fondasi yang kuat. Tetapi jika desa terus jadi sarang maling, maka jangan heran bila pusat kekuasaan pun terus dipenuhi pejabat busuk. Karena sejatinya, korupsi di Jakarta tidak lahir tiba-tiba ia lahir di desa, diberi makan oleh budaya permisif, lalu naik kelas hingga ke bangku kekuasaan yang lebih tinggi, jadi jangan heran ketika di atas budaya ini akan tetap ada.
Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Latest
Korupsi Desa Dibalik Kata “Uang Rokok”
Dari Trauma ke Harapan; Menakar Kepemimpinan Prabowo untuk Papua
Presiden Prabowo Menampar Muka KAPOLRI
Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Perlindungan Hukum atas Jaminan Benda
“Gebrakan Rp200 Triliun” Purbaya Sulit Mendorong Pertumbuhan Ekonomi